Tusuk Konde Retna
Hujan baru saja berhenti ketika Nayla sampai di rumah tua peninggalan Belanda itu. Jalan setapaknya licin, ditumbuhi lumut, dan pagar besinya berkarat seolah menolak siapa pun yang mencoba masuk. Di kejauhan, suara gamelan samar terdengar dari arah sawah. Tapi tidak ada acara apa pun malam itu.
Rumah itu berdiri sendiri di pinggir desa — temboknya pudar, jendelanya besar dengan kaca buram, dan di teras tergantung papan kayu bertuliskan “Dilarang Masuk Tanpa Izin Mbah Siti.”
Nayla menelan ludah. Ia seorang jurnalis muda yang sedang menulis artikel tentang benda pusaka perempuan Jawa. Teman redaksinya bilang, di rumah tua itu tersimpan barang peninggalan seorang bangsawan yang dulu terkenal akan kecantikannya — Nyai Retna Kartikasari.
“Cuma rumor,” kata temannya waktu itu. Tapi rasa penasaran Nayla lebih besar dari rasa takutnya.
Di dalam rumah, bau kayu lapuk bercampur harum kenanga yang samar. Dindingnya dihiasi foto-foto lama: pria Belanda berkumis tebal, wanita Jawa berbusana kebaya, dan satu foto besar di tengah — wajah seorang perempuan muda berkulit sawo matang dengan senyum lembut dan mata yang dalam.
“Cantik sekali…” gumam Nayla sambil menatap foto itu.
“Itu Nyai Retna.”
Nayla terlonjak. Dari arah pintu muncul seorang wanita tua memakai kebaya hitam, rambutnya disanggul rapi, bola matanya tajam tapi tenang.
“Saya Mbah Siti,” katanya pelan. “Penjaga rumah ini.”
Nayla menunduk sopan. “Saya Nayla, Mbah. Mau izin menulis tentang benda pusaka peninggalan Nyai Retna.”
Mbah Siti menatap lama, seolah membaca isi hati Nayla. Lalu ia berkata, “Kalau kamu cuma ingin tahu, boleh. Tapi jangan bawa apa-apa dari rumah ini. Karena yang tertinggal di sini bukan cuma barang.”
Sore itu mereka berbincang lama. Mbah Siti bercerita bahwa Nyai Retna dulunya adalah selir seorang pejabat Belanda. Cantik, pintar, tapi hidupnya berakhir tragis. Ia dituduh menyihir kekasihnya hingga mati.
“Sejak malam itu, rumah ini ditinggalkan. Tapi setiap Jumat Kliwon, ada yang menyalakan dupa sendiri di kamar atas,” bisik Mbah Siti.
Nayla mendengarkan sambil mencatat. Tapi matanya justru tertarik pada lemari tua di sudut ruangan — tertutup kain putih, tapi dari bawahnya memantul sedikit cahaya keemasan.
“Boleh saya lihat isinya, Mbah?”
Mbah Siti menggeleng cepat. “Jangan. Di situ ada tusuk konde milik Retna. Barang itu… bukan untuk manusia biasa.”
Namun malamnya, rasa penasaran Nayla mengalahkan nasihat itu.
Sekitar pukul dua belas malam, Nayla bangun karena mendengar suara seperti logam jatuh dari atas lemari. Ia menyalakan senter dan perlahan membuka kain putih itu.
Di dalamnya, di antara kain batik tua, terbaring sebuah tusuk konde emas berukir naga kecil di ujungnya. Ujungnya masih berkilau meski berdebu.
Saat jemarinya menyentuh benda itu, hawa dingin menyergap. Sekilas, ia melihat bayangan wanita berkebaya merah di kaca lemari. Tapi ketika ia menoleh, bayangan itu sudah hilang.
“Ah, mungkin halusinasi,” pikirnya.
Ia meletakkan tusuk konde di meja, lalu kembali tidur. Tapi malam itu, ia bermimpi menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri.
Dalam mimpinya, ia berada di ruangan penuh dupa. Di hadapannya duduk seorang pria Belanda dengan seragam lengkap. Di tangannya ada tusuk konde yang sama, dan di depan cermin besar, seorang wanita berkebaya merah tersenyum sedih.
“Retna…” suara pria itu gemetar. “Kita tidak bisa bersama.”
“Kalau begitu,” jawab wanita itu lembut, “biarlah konde ini yang menyatukan kita… di dunia lain.”
Tusuk konde itu menancap ke dada pria itu. Darah memercik. Wanita itu menjerit — lalu gelap.
Nayla terbangun dengan napas tersengal. Di dadanya, ada bekas goresan kecil seperti digores logam.
Keesokan harinya, Mbah Siti melihat wajah Nayla pucat.
“Kamu menyentuhnya, ya?”
Nayla diam.
Mbah Siti menunduk lirih. “Sudah terlambat. Sekali arwah Retna mengenali jiwamu, ia takkan pergi sebelum menyatu.”
“Kenapa saya, Mbah?”
“Karena kamu mirip dia. Sama-sama keras kepala dan… punya luka yang sama.”
Mbah Siti lalu menyalakan dupa, membacakan doa Jawa kuno yang membuat ruangan bergetar halus. Tapi dari cermin di dinding, Nayla melihat sosok wanita berkebaya merah tersenyum padanya — bukan pada Mbah Siti.
Malam kedua, gangguan semakin jelas. Suara langkah kaki di loteng, bayangan menari di cermin, dan suara lembut memanggil dari belakang,
“Nayla… ayo pulang.”
Ia melihat refleksi dirinya di kaca, tapi wajahnya bukan wajahnya — itu wajah Nyai Retna.
Nayla menjerit, menjatuhkan tusuk konde ke lantai. Tapi konde itu bergetar sendiri, lalu berdiri tegak menghadapnya.
Tiba-tiba, seolah kehilangan kendali, tangannya meraih benda itu dan menempelkannya di sanggul rambutnya.
Tubuhnya terasa ringan… seperti melayang.
Ketika Mbah Siti berlari masuk, Nayla sudah berdiri di depan cermin besar. Matanya menatap kosong, tapi senyumnya mirip dengan foto tua Nyai Retna di dinding.
“Retna! Lepaskan anak itu!” seru Mbah Siti sambil melempar bunga kenanga ke lantai.
Namun suara yang keluar dari mulut Nayla bukan suaranya sendiri.
“Aku tidak mencuri tubuh ini, Mbah. Aku hanya pulang ke rumahku.”
Cermin bergetar. Dupa di pojok ruangan menyala sendiri. Di luar, suara gamelan kembali terdengar.
Mbah Siti mencoba membaca mantra, tapi api dari dupa melompat dan membakar tirai. Dalam kekacauan itu, Nayla menatap cermin dan tersenyum puas.
“Dulu aku mati karena cinta. Sekarang aku hidup karena rindu.”
Ledakan kecil terdengar. Rumah itu terbakar habis.
Tiga hari kemudian, warga menemukan puing-puing hangus. Tidak ada jasad, hanya tusuk konde emas yang utuh berkilau di antara abu.
Polisi mengira itu pencurian barang antik yang berakhir kebakaran. Tapi Mbah Siti — yang selamat karena pingsan di halaman — tahu kebenarannya. Ia hanya menatap benda itu dengan mata basah.
“Retna sudah mendapatkan tubuh barunya,” bisiknya.
Sejak itu, beberapa warga mengaku melihat perempuan muda berkebaya merah berjalan di pinggir sawah saat senja. Wajahnya cantik, matanya sendu, dan di rambutnya tersemat tusuk konde naga emas yang berkilau di bawah cahaya sore.
Mereka bilang, kalau kamu menatap matanya terlalu lama, kamu akan mendengar bisikan lembut di telingamu:
“Cantik, ya… kondeku?”
Dan ketika kamu menoleh, yang tertinggal hanyalah aroma kenanga yang tak mau hilang sampai pagi.
🪶 Akhir yang tragis bukan sekadar kematian, tapi ketika jiwa yang lama kembali hidup melalui tubuh yang baru…
Share this content:

Neng Hifda
Menulis adalah sebuah hobi yang tidak bisa di tinggalkan, Terimakasih Sukanulis.com situs yang bisa menyalurkan Hobiku.






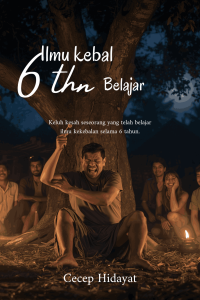


Post Comment