Diberi Kesempatan Kedua oleh Mantan
Hujan sore itu turun tanpa kompromi. Jalanan dipenuhi genangan, dan langit seperti menyembunyikan semua cahaya. Raka menatap ke luar jendela kamar kosnya, melihat butiran air jatuh seperti ritme masa lalu yang berulang-ulang.
Di tangannya, ponsel bergetar pelan — sebuah pesan dari nomor yang dulu ia hapus dengan penuh emosi.
“Bisa ketemu bentar? Aku di kafe dekat kampus. Penting.”
— Nadia.
Raka terdiam cukup lama. Nama itu seperti pisau tumpul: tak lagi tajam, tapi masih bisa melukai. Sudah dua tahun sejak perpisahan yang nggak pernah benar-benar ia pahami. Dua tahun sejak Nadia memilih pergi, tanpa penjelasan yang cukup.
Tapi sekarang, dia menghubungi lagi.
Dan meski logika berteriak “jangan datang”, hatinya tetap mengambil jaket dan kunci motor.
Pertemuan yang Terlambat
Kafe itu masih sama seperti dulu — dinding bata merah, aroma kopi yang lembut, dan lagu-lagu lawas yang mengisi ruang kosong. Raka melihat Nadia duduk di sudut, mengenakan sweater abu dan rambut yang kini lebih panjang dari terakhir kali mereka bertemu.
Ia masih secantik dulu, tapi ada sesuatu yang lain di matanya: lelah.
“Masih inget kopi favoritku,” kata Raka, sambil menunjuk cangkir cappuccino di depannya.
Nadia tersenyum samar. “Aku nggak lupa hal-hal kecil, Rak. Cuma waktu itu… aku harus pergi.”
Raka duduk. “Harus pergi atau milih pergi?”
Pertanyaan itu menggantung. Nadia menunduk, jari-jarinya meremas ujung lengan sweater.
“Waktu itu aku nggak kuat lihat kamu terus berjuang sendirian. Aku pikir kalau aku pergi, kamu bakal lebih fokus ke kariermu.”
Raka tertawa getir. “Jadi kamu ninggalin aku… demi aku?”
Nadia mengangkat pandangan. Matanya basah. “Aku salah, Rak. Aku pikir cinta bisa disimpan di tempat aman dan nanti aku tinggal balik lagi. Tapi ternyata… nggak sesederhana itu.”
Keheningan menggantung cukup lama. Hanya suara hujan di luar yang mengisi ruang di antara mereka.
Sakit yang Tak Sembuh
Raka menatapnya lama, lalu berkata lirih, “Kamu tahu nggak, selama kamu pergi, aku ngerasa kayak hidup tapi nggak bener-bener hidup. Aku kerja, ketawa, nongkrong sama temen, tapi semuanya hambar.”
Ia berhenti sejenak, menatap jari-jarinya sendiri.
“Dan tiap malam, aku cuma nanya hal yang sama di kepala: ‘Salahku apa?’”
Nadia menggigit bibir bawahnya, matanya mulai berair. “Salah kamu cuma satu, Rak. Kamu terlalu sayang sama aku. Dan aku terlalu pengecut buat ngakuin kalau aku juga takut kehilangan kamu.”
Air mata itu akhirnya jatuh, menelusuri pipinya yang dulu selalu Raka hapus dengan ibu jari.
“Tapi sekarang aku balik bukan buat minta dimaafin,” lanjut Nadia. “Aku balik karena aku sadar, nggak semua orang dikasih kesempatan kedua. Dan kalau aku masih punya satu… aku mau itu sama kamu.”
Antara Benci dan Rindu
Raka berdiri. Dadanya sesak. Ia ingin memeluknya, tapi juga ingin berteriak.
“Gampang banget ya kamu ngomong begitu,” katanya, suaranya bergetar.
“Kamu pergi tanpa alasan jelas, ninggalin aku di titik terendah, terus sekarang balik kayak nggak terjadi apa-apa.”
Nadia menatapnya. “Aku ngerti kamu marah. Aku juga benci diriku sendiri karena ninggalin kamu.”
“Benci?” Raka menatapnya tajam. “Kamu nggak tahu gimana rasanya ngelihat orang yang kamu cinta tiba-tiba hilang, tanpa pamit, tanpa pesan, cuma ninggalin aku sama kenangan yang tiap malam nyiksa!”
Nadia menunduk, air matanya jatuh ke meja. “Aku tahu, Rak. Aku pantas dibenci.”
Raka menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di balik amarah itu, ada kerinduan yang nggak bisa ia sembunyikan. Ia masih mencintai perempuan itu — dan itu justru yang paling menyakitkan.
Dua Tahun Terlewat
Hujan berhenti. Mereka pindah duduk ke kursi dekat jendela, menatap sisa-sisa air yang menetes dari kanopi.
Perbincangan berlanjut, lebih tenang kali ini. Nadia cerita kalau selama dua tahun itu, ia pindah ke Jogja untuk ngurus ibunya yang sakit keras.
“Aku sempat nggak punya waktu buat siapa-siapa, Rak. Bahkan buat diriku sendiri,” ucapnya pelan.
“Dan kamu nggak sempat ngabarin aku?” tanya Raka.
Nadia menggeleng. “Aku takut kamu datang. Takut kamu tinggalin semua buat aku. Aku nggak mau kamu ngerasa terikat sama kesedihanku.”
Raka terdiam. Kali ini amarahnya perlahan berubah jadi iba.
Ia menatap wajah perempuan itu lama-lama, dan di situ ia lihat sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari: ketulusan yang terluka.
Kesempatan Kedua
Hari itu berakhir dengan obrolan panjang. Mereka tertawa, saling melempar ingatan tentang masa lalu yang manis — nonton film di emperan mall karena kehabisan uang, atau nyasar ke Subang gara-gara salah jalan saat mau ke Lembang.
Raka baru sadar, tawa Nadia masih sama. Dan hatinya pun pelan-pelan luluh.
Sebelum berpisah, Nadia menatapnya dan berkata, “Aku nggak minta semuanya kembali kayak dulu. Aku cuma minta… kesempatan buat nebus semua yang salah.”
Raka menatapnya lama. “Kamu yakin nggak bakal pergi lagi?”
“Aku nggak janji nggak akan pergi, Rak,” kata Nadia. “Tapi kalau aku pergi lagi, aku bakal kasih tahu alasannya.”
Raka tersenyum getir, tapi hangat. “Itu udah lebih dari cukup.”
Waktu yang Menyembuhkan
Minggu demi minggu berlalu. Mereka mulai sering bertemu lagi. Awalnya canggung, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Kadang Raka datang ke toko buku tempat Nadia kerja, kadang mereka cuma duduk di taman sambil makan gorengan dan bicara hal-hal sederhana.
Cinta mereka seperti api kecil yang dulu padam, kini menyala lagi — tapi kali ini lebih tenang, nggak membakar, cuma menghangatkan.
Namun tidak semuanya berjalan mulus. Ada hari ketika rasa takut kembali datang.
Suatu malam, Nadia tiba-tiba tak membalas pesan. Raka gelisah. Bayangan masa lalu datang lagi, dan pikirannya berputar: jangan-jangan dia pergi lagi?
Tapi sebelum ia sempat menekan nomor Nadia, sebuah pesan masuk.
“Aku lagi di rumah sakit, Rak. Ibu kambuh. Aku butuh kamu.”
Tanpa pikir panjang, Raka langsung meluncur ke rumah sakit. Begitu sampai, ia menemukan Nadia duduk di kursi tunggu, mata sembab, tangan dingin.
Tanpa berkata apa-apa, ia memeluknya.
Pelukan yang tak butuh kata, hanya kehadiran.
Langit Cerah di Akhir Hujan
Beberapa bulan kemudian, ibunda Nadia membaik. Hari-hari yang dulu penuh tangis berganti jadi pagi yang tenang.
Suatu sore di taman kota, Nadia menatap Raka sambil tersenyum. “Kamu tahu nggak, dulu aku selalu takut nyakitin kamu. Tapi ternyata, selama ini aku yang nyiksa diriku sendiri.”
Raka menggenggam tangannya. “Aku juga baru sadar, kadang kita harus ngerasain kehilangan dulu biar ngerti cara menjaga.”
Nadia menatap matanya. “Jadi… kamu udah maafin aku?”
Raka mengangguk pelan. “Udah. Karena cinta yang nggak dimaafin, nggak akan pernah tumbuh lagi.”
Air mata Nadia menetes, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menunduk, lalu berbisik lirih,
“Terima kasih udah kasih aku kesempatan kedua.”
Raka tersenyum, mencium punggung tangannya.
“Bukan aku yang ngasih kesempatan, Ran. Tapi waktu.”
Langit sore itu berwarna oranye lembut. Hujan yang dulu membawa perpisahan, kini jadi saksi pertemuan yang baru.
Dan di bawah langit yang mulai gelap, dua hati yang pernah patah akhirnya menemukan rumahnya lagi.
Epilog: Setelah Semua Luka
Setahun kemudian, Raka dan Nadia berdiri di depan rumah kecil di pinggiran kota. Di halaman, pot-pot bunga berbaris rapi — hasil tangan Nadia sendiri.
Ia menatap Raka sambil tertawa, “Kamu sadar nggak? Hujan turun tiap kali kita mulai sesuatu yang baru.”
Raka merangkulnya dari belakang. “Mungkin karena Tuhan tahu, kita cuma bisa tumbuh setelah badai.”
Hujan benar-benar turun — lembut kali ini, bukan deras. Mereka berdiri di bawahnya, tak lagi bersembunyi.
Cinta yang dulu hancur kini tumbuh kembali, bukan karena lupa, tapi karena mereka belajar memaafkan.
Dan di tengah rinai hujan, Nadia berbisik:
“Kesempatan kedua ini… nggak akan aku sia-siain.”
Raka menjawab pelan, “Aku juga, Ran. Karena kali ini, aku nggak mau kehilangan lagi.”
Baca Juga : Saat Hujan Turun di Bulan Oktober
Share this content:





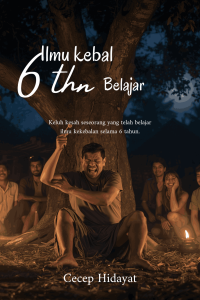


Post Comment