Bab 1: Cahaya di Tengah Hujan
Hujan turun deras malam itu, mengetuk genteng rumah tua di tepi kota seperti ribuan jari yang tak sabar. Jalanan basah berkilau memantulkan lampu jalan yang redup, membuat suasana seperti dunia lain—sunyi, dingin, tapi terasa ada sesuatu yang mengintai.
Arga menyalakan rokoknya di teras, pandangan kosong ke arah jalan yang sepi. Api di ujung batang rokok berkelip sebentar sebelum redup, nyaris kalah oleh hembusan angin basah. Malam-malam begini, pikirannya selalu kembali ke hal-hal lama—kenangan yang seharusnya sudah dikubur tapi justru makin sering datang menghantui.
“Besok harusnya aku berangkat ke Jogja,” gumamnya pelan. “Tapi kenapa rasanya… kayak ada yang nyuruh tetap di sini?”
Suaranya tenggelam oleh raungan guntur.
Rumah tua itu peninggalan kakeknya, seorang lelaki yang terkenal aneh di kampung. Katanya dulu kakeknya sering menghilang berhari-hari lalu pulang dengan mata merah dan tubuh letih, seperti habis menempuh perjalanan panjang. Tapi anehnya, kaki dan bajunya selalu bersih—seolah perjalanan itu bukan di dunia nyata.
Arga dulu menganggap semua cerita itu omong kosong. Tapi malam ini, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri.
Dari ujung jalan, cahaya kecil melintas cepat, terlalu terang untuk sekadar pantulan lampu jalan. Cahaya itu bergerak mendekat, lalu berhenti tepat di depan rumahnya.
Arga refleks berdiri, rokoknya jatuh ke tanah.
Cahaya itu bukan mobil, bukan motor, bukan juga lampu senter. Ia melayang setinggi dada orang dewasa, berwarna biru keperakan, berdenyut seperti jantung yang hidup. Semakin lama, semakin jelas bentuknya: bola cahaya sebesar kepala manusia, berputar perlahan, memancarkan percikan halus yang jatuh ke tanah seperti debu bintang.
Jantung Arga berdegup kencang.
“Apaan tuh…” bisiknya.
Cahaya itu bergerak mendekat, melewati pagar rumahnya tanpa hambatan, seakan besi tua berkarat itu tak nyata. Arga mundur satu langkah, lalu dua langkah, tapi bola cahaya terus mendekat. Entah kenapa, meski takut, kakinya seolah terpaku di tempat.
Lalu terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan juga suara mesin. Suara itu langsung muncul di dalam kepalanya, jernih, dalam, tapi terasa asing.
“Arga…”
Ia terbelalak. “Siapa?”
“Waktu kita terbatas. Dengarkan baik-baik.”
Arga mencoba mengedipkan mata, berharap ini hanya ilusi karena terlalu banyak kopi dan kurang tidur. Tapi cahaya itu tetap ada, makin dekat, hingga hanya berjarak satu meter darinya.
Bola cahaya itu berdenyut sekali, lalu memancarkan kilatan yang membuat seisi teras rumah terang seperti siang. Saat itu, Arga melihat sekilas bayangan wajah seorang perempuan muda di dalamnya—wajah pucat, mata tajam, dan bibir yang seolah berbisik namanya.
Deg! Jantung Arga hampir copot.
“Siapa lo?!” teriaknya.
Tak ada jawaban. Cahaya itu justru melesat masuk ke dalam rumah, menembus pintu kayu tua seakan tak ada penghalang. Arga panik, buru-buru masuk ke dalam, berlari menembus ruang tamu yang remang.
Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku.
Bola cahaya itu berhenti di ruang tengah, tepat di depan lemari tua milik kakeknya. Lemari itu sudah lama dikunci, bahkan kuncinya hilang entah ke mana. Tapi sekarang, tanpa disentuh, pintu lemari itu terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang.
Di dalamnya, bukan pakaian, bukan barang antik. Melainkan sebuah buku tua bersampul kulit, tebal, dengan lambang aneh yang tercetak di permukaannya—sebuah lingkaran dengan tiga garis silang, mirip simbol kuno.
Cahaya itu berputar sekali di atas buku, lalu meredup, menyusut, hingga akhirnya padam seketika. Hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada.
Arga berdiri terpaku. Ruangan kembali gelap, hanya ditemani suara hujan di luar.
Pelan-pelan, ia mendekati lemari. Tangannya bergetar saat meraih buku itu. Kulitnya terasa dingin, nyaris membeku, tapi entah kenapa ada rasa hangat yang menjalar ke tubuhnya begitu menyentuhnya.
Ia membuka sampul pertama.
Tulisan tangan memenuhi halaman, dengan bahasa yang tak sepenuhnya ia kenali. Ada huruf Jawa kuno, ada latin, ada simbol yang bahkan belum pernah ia lihat. Tapi di tengah halaman, ada sebuah kalimat yang jelas, ditulis dengan bahasa Indonesia modern:
“Jika kau membaca ini, berarti waktumu sudah tiba.”
Arga langsung merinding.
Suara guntur kembali menggelegar di luar.
Lalu, tiba-tiba, semua lampu di rumahnya padam.
Gelap total.
Arga menjatuhkan buku itu ke lantai, lalu meraba ponselnya di saku. Saat menyalakan flashlight, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Di cermin tua di dinding ruang tengah, ada pantulan wajah—bukan wajahnya, tapi wajah perempuan yang tadi muncul di dalam cahaya. Rambut panjang, mata hitam dalam, dan bibir tipis yang bergerak tanpa suara.
Arga terpaku, kakinya kaku.
Perempuan itu mengangkat jarinya, menunjuk tepat ke arah buku di lantai.
Flashlight ponselnya bergetar, layar tiba-tiba mati meski baterai penuh. Rumah kembali tenggelam dalam kegelapan pekat. Tapi dari bawah, buku itu mengeluarkan cahaya samar, seakan memanggil.
Arga merunduk, memungutnya lagi dengan tangan gemetar. Begitu buku itu menyentuh kulitnya, kilatan cahaya biru meledak memenuhi ruangan, menyilaukan mata.
Dan dalam sekejap, Arga tak lagi berada di ruang tengah rumah tuanya.
Ia berdiri di sebuah jalan batu yang asing, dikelilingi hutan lebat dengan pepohonan raksasa yang tak pernah ia lihat di dunia nyata. Langitnya berwarna ungu gelap, dihiasi bulan raksasa yang menggantung rendah.
Udara asing, dingin, penuh aroma tanah basah.
Arga terengah, menoleh ke sekeliling. “Apa-apaan ini…”
Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. Ia menoleh cepat, dan mendapati sosok perempuan itu berdiri beberapa meter darinya. Kali ini jelas—ia nyata, bukan sekadar pantulan atau wajah di cahaya. Bajunya putih lusuh, wajahnya pucat, tapi matanya penuh cahaya.
“Kamu… siapa?” tanya Arga dengan suara serak.
Perempuan itu melangkah mendekat.
“Aku penjaga,” jawabnya lirih. “Dan kamu… pewaris.”
Arga terbelalak. “Pewaris apa?!”
Perempuan itu menatapnya lama, lalu menunjuk buku yang masih erat digenggamnya.
“Itu bukan sekadar buku, Arga. Itu kunci. Dan malam ini, kamu sudah membukanya. Tak ada jalan kembali.”
Arga menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat.
Di kejauhan, terdengar suara raungan rendah—seperti binatang buas, tapi bercampur dengan suara logam beradu. Suara itu makin lama makin dekat.
Perempuan itu menatap Arga dengan serius.
“Kamu harus memilih. Bertahan di sini, atau kembali… dengan konsekuensi yang lebih besar.”
Arga terdiam, otaknya berputar cepat mencari jawaban. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, raungan itu pecah menjadi teriakan keras yang mengguncang hutan, membuat tanah di bawah kakinya bergetar.
Arga menoleh, dan dari balik pepohonan gelap, sosok hitam raksasa muncul dengan mata merah menyala.
Share this content:



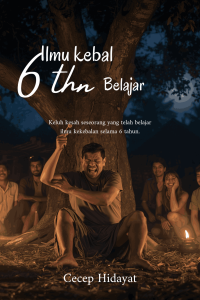


Post Comment